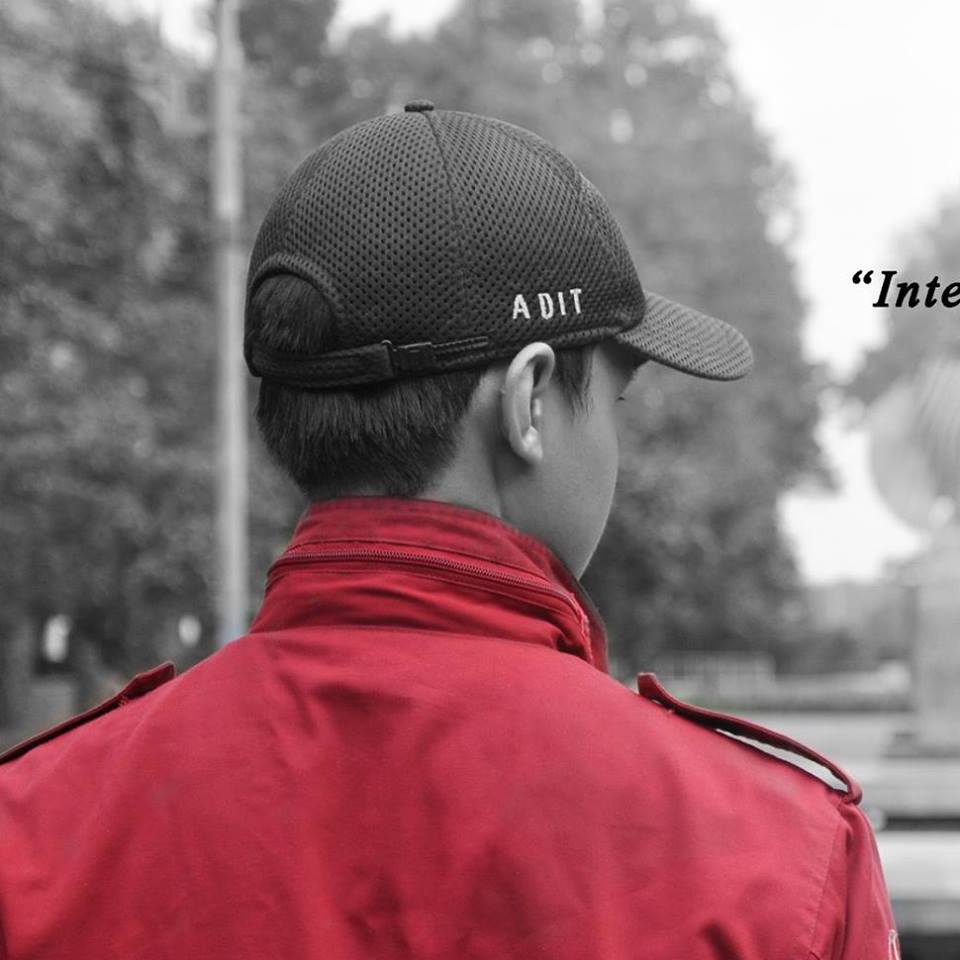Menuju Dunia Pasca Literasi
- 37 mins“Reading and writing are doomed. Literacy as we know it is over. Welcome to the post-literate future.
Tiga kalimat di atas mungkin terasa hiperbolis, namun layak untuk direnungi, dikaji, dan diperdalam lebih lanjut. Kalimat yang begitu provokatif tersebut ditulis oleh Michael Ridley di halaman depan web-based project bernama Beyond Literacy yang ia bangun sejak 2012 lalu. Proyek ini merupakan sebuah eksperimen untuk membuka ruang diskursus mengenai fenomena yang terjadi secara global di dunia literasi. Ridley tidak mengajukan banyak hal, hanya sebuah kemungkinan bahwa akan tergantikannya aksara dengan sesuatu lain, yang ia belum tahu apa, dan hal itu akan merevolusi manusia secara masif dan total sebagaimana dahulu literasi merevolusi manusia bertradsi lisan.
Fenomena apa yang sebenarnya Ridley maksud? Dalam era dimana teknologi sudah mencapai titik yang semakin sukar untuk dipahami, dimana machine learning sudah menjadi kenyataan, dimana virtual reality akan masuk sebagai perangkat keseharian, ataupun dimana google lebih mengerti diri kita sesungguhnya ketimbang kita sendiri, kemungkinan (atau kenyataan) bahwa literasi akan segera memasuki wujud baru bukan lagi hanya tuduhan, klaim, ataupun provokasi tak berdasar. Mulai dari level anak kecil hingga orang dewasa, membaca buku bukan lagi suatu hal yang melebur dalam kehidupan sehari-hari. Untuk belajar sesuatu, Youtube dan berbagai online course lain mungkin akan lebih bisa memfasilitasi dengan tingkat kejelasan dan kefektifan yang tinggi. Orang tidak perlu membaca Das Kapital untuk memahami komunisme, atau tidak perlu membaca Being and Time untuk memahami eksistensialisme Heidegger, tidak perlu membaca Origin of Species untuk memahami teori evolusi Darwin. Informasi sekilas, meskpun hanya berupa teks singkat sekian paragraf, atau video penjelasan yang ringkas, atau doktrin serta ajaran yang dberikan oleh otoritas, yang entah ditulis atau dibuat oleh siapa dengan latar belakang apa, mendominasi basis pengetahuan ketimbang kedalaman ilmu yang sesungguhnya. Dalam hal ini, teks menjad mandul, ia kehilangan otoritasnya.
Dalam sisi praksisnya sendiri, begitu banyak dilema dan polemik yang terjadi di dunia perbukuan, penerbitan, dan kepenulisan, yang membuat literasi tidak mencapai energi optimumnya. Seorang pegiat literasi, M. Iqbal Dawami, bahkan menyebut keadaan ini sebagai Pseudoliterasi, keadaan dimana literasi hanya mewujud dalam rupa yang semu, gadungan, tidak utuh. Buku terkapitalisasi secara ironis, pendidikan terasing dengan budaya baca-tulis, penulis terkikis oleh tuntutan pasar ketimbang jujur terhadap ide dan pemikiran, dan masih banyak lagi. Masyarakat pun lebih banyak yang aliterasi (keadaan dimana seseorang mampu membaca, namun tidak tetarik untuk melakukannya) ketimbang literasi secara epsitemik, literasi utuh yang menubuh bersama keseharian, bukan sekadar bisa baca papan pengumuman pinggir jalan belaka. Sayangnya, tren aliterasi ini tidak hanya menjangkit masyarakat menengah kebawah, namun juga masyarakat kelas atas dengan kesibukan kantorannya yang terasing dengan kebiasaan membaca selain laporan proyek ataupun setumpuk administrasi. Perlu diketahui, berdasarkan laporan UNESCO tahun 2015, literacy rate Indonesia mencapai 93.9% dan seharusnya sampai tahun ini telah meningkat. Cukup paradoks jika dilihat sekilas, namun memang kenyataannya literasi tidak lah serta merta mencerminkan kemajuan begitu saja, apalagi jika pengukurnya hanyalah melek aksara. Pada tulisan yang lain telah saya jelaskan bahwa literasi tidaklah sesederhana itu (baca: Literasi Bukanlah Keberaksaraan)
Mengingat fenomena yang kita hadapi ini terjadi setelah kejayaan literasi, akan tetapi ia berbeda dari literasi, maka mungkin cukup pantas kita menyebutnya pasca-literasi atau pos-literasi. Fenomena ini seperti mendapampingi posmodernisme dalam kebaharuan yang mengoreksi modernisme. Dalam hal ini, literasi dan modernisme mungkin tidak bisa disejajarkan, namun bila ditinjau lebih detail bagaimana dua komponen ini mendampingi sejarah, bisa jadi ia merupakan hal yang setara. Penyebutan kata pasca- atau pos- disini mungkin bisa memberi dampak kontroversial sebagaimana istilah posmodernisme mengalami polemik makna. Adanya prefiks pasca- membuatnya seakan berbeda total dari literasi yang sesungguhnya, sedangkan fenomena ini sendiri belum bisa kita pahami dengan baik. Seandainya literasi itu tidak hilang sepenuhnya, namun mentransformasi diri ke wujud yang berbeda, mungkin akan lebih tepat jika menyebut wujud baru itu sebagai neo-literasi. Akan tetapi, kita lupakan dahulu polemik istilah, mari kita coba pahami apa yang sesungguhnya tengah terjadi.
Meninjau kembali Kelisanan
Sebelum melihat ke masa yang akan datang, atau masa yang akan kita hadapi, peninjauan kembali bagaimana literasi hadir dalam peradaban manusia, dan bagaimana dampaknya secara menyeluruh dalam kehidupan manusia mungkin perlu dilakukan. Bagi kita yang sudah sejak kecil berinteraksi dengan aksara, mungkin membayangkan masa ketika aksara belum ada sama sekali dalam kehidupan manusia bukan hal yang mudah, mengingat pada dasarnya, aksara itu sendiri mentransformasi struktur pikiran manusia hingga bisa berubah total ketimbang manusia dengan tradisi lisan.
Lahirnya literasi sesungguhnya sukar untuk ditetapkan titik tepatnya. Aksara pertama yang ditemukan arekologis adalah aksara paku (cuneiform) dari Mesopotamia yang berumur sekitar 6000 tahun silam. Akan tetapi, penggunaan aksara pada masa itu masihlah sangat terbatas. Kebutuhan akan aksara yang ada pada saat itu hanyalah untuk keperluan pengelolaan struktur sosial, seperti pengaturan hukum dan transaksi ekonomi. Hal ini pun membuat aksara di awal mula hidupnya masihlah berada dalam restriksi otoritas. Jared Diamond dalam Guns, Germs, and Steel, menjelaskan bahwa “tulisan awal dibuat demi memenuhi kebutuhan lembaga-lembaga politik itu, dan para penggunanya adalah birokrat purnawaktu yang melahap simpanan makanan berlebih hasil budidaya para petani yang memproduksi makanan.” Hal ini membuat penggunaan aksara tidaklah seperti apa yang kita bayangkan, dimana setiap individu dapat menulis dan membaca, sehingga lahirnya aksara pada dasarnya tidak bisa disebut sebagai lahirnya literasi.
Tradisi lisan dengan demikian masih menempel erat dalam kehidupan manusia hingga beratus tahun setelah ditemukannya aksara pertama kali. Ini juga membuat batas antara literasi dan kelisanan sesungguhnya cukup sukar untuk ditelisik. Kapan sesungguhnya literasi terjadi, dan seberapa besar dampak literasi merupakan misteri yang cukup besar, hingga kemudian Walter J. Ong, seorang professor sastra inggris, cukup mampu mengungkapkannya dalam bukunya Kelisanan dan Keberaksaraan. Ia mengatakan sulitnya melihat batas ini adalah karena di zaman sekarang ini, mencari masyarakat yang murni lisan (tidak tersentuh aksara sedikit pun) sangatlah sulit. Identifikasi tradisi lisan bisa dilihat dari ciri paling utamanya, yakni basis indra yang digunakan.
Tradisi lisan sangat berpusat pada pendengaran, sangat kontras dengan literasi yang berpusat pada penglihatan. Suara, hadir secara unik dalam bingkai waktu. Informasi yang keluar dari suara hanya bisa didengar saat itu juga, tepat saat itu. Saat saya berkata “Literasi”, maka ketika saya mencapai suku kata “-te-“, maka “Li-“ sudah lenyap, dan demikian seterusnya. Ditambah lagi, telinga, sensor suara, bersifat memusatkan dan mengumpulkan, tidak stereotip seperti mata. Ketika kita mendengar, seluruh suara yang ada di sekliling kita saat itu akan masuk semua ke dalam telinga, sedangkan tidak untuk mata. Hal ini membuat suara begitu utuh dan menyeluruh, begitu kontekstual. Selain itu, suara juga memiliki interioritas yang membuatnya melebur bersama pengalaman sang pemilik suara, sehingga seakan seluruh kosmos adalah peristiwa yang berlangsung dimana manusia adalah pusatnya sekaligus bagian darinya. Ini berbeda dengan budaya literasi dimana informasi hadir dalam teks yang mewujud secara materiil dan terpisah, sehingga informasi itu tercerabut dari seluruh jagad kontekstualnya dan akhirnya dunia hanyalah obyek yang ada di depan mata. Semua itu berefek pada daya pikir masyarakat literasi yang cenderung memilah, memisah, memecah, menganalisis, membedakan, dan mengelompokkan yang merupakan syarat perlu sebuah pikiran kritis, obyektif, dan abstrak. Tradisi lisan bersifat lebih kontekstual, konkret, subyektif, menyatu bersama kehidupan dan keseharian, serta bertendensi pada kelompok ketimbang individu. Selain itu, tradisi lisan lebih reaksioner karena sangat terkait dengan kejadian langsung, tanpa ada jeda atau medium apapun. Di sisi lain, budaya literasi lebih berjarak, sehingga informasi yang masuk akan melalui wilayah refleksi dan interpretasi kritis terlebih dahulu sebelum menghasilkan reaksi. Kita tidak mungkin tiba-tiba memarahi penulis ketika tengah membaca buku yang ditulisnya.
Efek ini mungkin terkesan sederhana, namun ia sangat mendasar dan kontras sehingga sesungguhnya literasi mengubah radikal pikiran manusia. Salah satu penelitian dari Alexander Luria pada 1931 terhadap beberapa subyek buta huruf (yang bisa mewakli masyarakat bertradisi lisan), sebagaimana dikutip oleh Ong sendiri, menunjukkan hal ini secara jelas. Ketika Luria mencoba menunjukkan beragam bentuk geometris, subyek tersebut lebih mengidentifikasinya dengan hal-hal yang terkait dengan kehidupannya secara konkrit, seperti lingkaran akan disebut sebagai piring, saringan, ember, atau rembulan. Selain itu, ketika diberi pertanyaan “Di Utara Jauh yang bersaljur, semua beruang berwarna putih. Novaya Zembla berada di Utara Jauh dan di sana selalu bersalju. Apa warna beruangnya?”, maka jawabannya adalah “Saya tidak tahu, saya pernahnya melihat beruang warna hitam, tidak pernah selain itu. Tiap daerah punya jenis binatang sendiri”. Atau, ketika Luria meminta definisi dari pohon, ia justru mendapat perlawanan berupa tanggapan “mengapa saya harus melakukannya? Semua orang tahu apa pohon itu, mereka tidak perlu saya beri tahu.” Selain itu, Luria pun mencoba menanyakan hal yang lebih bersifat kedirian dengan mengatakan “Apakah anda puas dengan diri Anda atau apakah Anda ingin berubah?”, yang dijawab dengan “Akan menyenangkan jika saya punya lebih banyak tanah dan bisa menanam gandum.” Luria pun menambahkan “Apa kekurangan-kekurangan Anda?”, yang dijawab dengan “Yah, orang kan berbeda-beda- ada yang tenang, pemarah, atau kadang-kadang ingatannya payah…”, atau “Kami berperilaku baik—kalau kami orang jahat, tidak akan ada yang menghargai kami.”
Penelitian Luria di atas menunjukkan bahwa pola pikir masyarakat lisan cenderung situasional dan kontekstual. Hal ini pun membuat segala pengetahuan selalu kembali ke personal, sehingga membuat pertarungan ego dalam masyarakat literasi lebih langsung dan spontan. Sedangkan, di masyarakat literasi, antara yang diketahui dan yang mengetahui terpisah. Pola tribalitas, kecendrungan untuk secara subyektif melihat kelompok, juga terlihat jelas. Individualitas tidak dikenal dalam masyarakat lisan, karena setiap diri adalah bagian dari suatu hal yang lebih besar. “Aku” hanyalah konsep yang muncul kemudian hari, ketika subyek bercerai dengan obyek.
Apa sesungguhnya yang kemudian membuat semua pola pikir lisan yang dijelaskan di atas berubah total? Dan kapan? Hal ini sesungguhnya masih berada di wilayah perdebatan. Perjalanan berkembangnya sistem aksara bukanlah perjalanan singkat, karena menciptakan suatu sistem tanda yang bisa mewakili suara yang diucap oleh suatu masyarakat bukanlah hal yang mudah. Perubahan radikal akan sistem aksara terjadi ketika terciptanya alfabet di Yunani pertama kali sebagai turunan dari aksara Ibrani. Diamond mengatakan bahwa alfabet Romawi (Yunani) merupakan produk akhir serangkaian panjang penyalinan cetakbiru (aksara). Alfabet Yunani begitu berbeda dengan sistem aksara lain karena ia sistem pertama yang memisahkan konsonan dengan vokal sedemikian sehingga setiap satu bentuk suara hanya diwakili satu tanda, berbeda dengan sistem-sistem sebelumnya, seperti silabari atau logograf, yang masih memberi tanda hanya pada satu kata atau satu suku kata. Hal ini begitu penting sehingga dikatakan oleh Eric Havelock dalam Origins of Western Literacy bahwa transformasi teramat penting yang nyaris total terhadap kata dari suara ke penglihatan inilah yang memberi budaya Yunani keunggulan intelektual atas budaya-budaya kuno lainnya. Alfabet Yunani memecah suara lebih abstrak sehingga secara psikologis mempengaruhi cara berpikir mereka. Hal ini menjelaskan mengapa kemudian filsafat, serta semua turunannya, dalam bentuk klasiknya muncul pertama kali di Yunani, bukan di Cina atau Mesoamerika.
Pada titik inilah kita bisa mengatakan literasi cerai sepenuhnya dari lisan dan menjadi diri sendiri. Memang sayang kemudian, dinamika peradaban dunia kala itu masih penuh dengan perang dan penjajahan wilayah sehingga bangkitnya literasi dari Yunani ini tidak bisa berkembang dengan maksimal. Keterbatasan yang dimunculkan oleh otoritas penguasa membuat literasi sempat dormant hingga Renaissance, yang kemudian terlahir kembali bersama modernisme (paling tidak berdasarkan Barat, karena sesungguhnya literasi berkembang cukup pesat di belahan lain dunia ketika Barat mengalami kegelapan). Karena ciri khas pola pikir literasi adalah keberjarakan dan keterlepasan, itu juga yang kemudian menjadi ciri khas modernisme ketika pertama kali diinisiasi oleh Rene Descartes. Dikotomi subyek-obyek semakin nyata dan jelas, diri semakin lepas terisolasi dari dunia, dan pencarian akan obyektifikasi total segala sesuatu. Dari sini, individualitas pun tumbuh subur diikuti dengan pengagungan besar-besaran terhadap rasionalitas dan ilmu pengetahuan. Literasi kemudian mencapai puncak kejayaannya ketika penemuan mesin cetak oleh Johanes Gutenberg. Pikiran manusia semakin bisa dengan mudah direproduksi dan diabadikan, menumbuh suburkan dialektika pemikiran yang tak terbatas ruang dan waktu dan semakin membuat teks lebih otoritatif ketimbang pembuatnya.
Dapat dilihat dari narasi perjalanan literasi tersebut bahwa pada dasarnya modernisme (dalam konteks filsafat dan pemikiran) sesungguhnya berlandaskan pada literasi yang juga lahir kembali ketika teks tidak lagi dikuasai otoritas tertentu. Jika kita lihat bagaimana restriksi yang dimunculkan oleh penguasa menjadi salah satu sebab lambatnya perkembangan aksara ketika muncul pertama kali di Mesopotamia, maka bukanlah hal yang mengherankan kemudian ketika literasi pun terhambat perkembangannya juga disebabkan oleh restriksi penguasa. Meskipun pada saat itu (zaman kegelapan barat), literasi tumbuh subur di belahan lain dunia, efeknya terkalahkan oleh dominasi barat yang muncul kemudian. Selain itu, reproduksi teks pada masa itu sangatlah sulit mengingat mesin cetak belum ditemukan, sehingga satu-satunya cara teks bereproduksi adalah penulisan ulang secara telaten. Terlepas dari hal itu, menarik untuk dilihat kemudian bahwa runtuhnya modernisme dalam kritik posmodernisme bersanding dengan munculnya fenomena baru di dunia literasi. Meskipun jelas sebab dan asal-usulnya fenomena itu tidak lah sederhana, karena menyangkut berbagai aspek, terutama perkembangan teknologi. Jika posmodernisme seakan ‘disengaja’ karena dipicu oleh manusia itu sendiri, yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap keagungan narasi besar modernisme, fenomena pasca-literasi seakan muncul secara natural sebagaimana literasi lahir secara natural sebagai efek langsung dari berkembangnya agrikultur dan hirarki masyarakat.
Hiperteks, Sebuah Era Baru
Sebelumnya saya mohon maaf untuk anak yang berkelut di bidang teknologi informasi karena saya mengadopsi istilah mereka untuk pemaknaan lain. Hiperteks di sini bukanlah teks pembangun halaman di internet. Dalam hal ini, saya menyebut hiperteks sebagai teks bentuk baru, teks yang tidak sekadar aksara, teks yang telah memperluas makna literasi menjadi apa yang kemudian disebut dengan transliterasi. Munculnya hiperteks, sebagai konsekuensi logis dari berkembangnya teknologi multimedia yang sangat terinterkoneksi, menariknya, memunculkan beberapa dampak yang berpengaruh juga pada pola pikir manusia, sebagaimana dulu literasi mempengaruhi pola pikir manusia.
Pada tahap awalnya, menyampaikan informasi dari satu belahan dunia ke belahan lain haruslah murni menggunakan teks tertulis. Itu pun memakan waktu yang tidak sebentar. Antara penyampai informasi dan penerima informasi terpisah jarak dan waktu, yang sesungguhnya merupakan ciri paling khas dari literasi. Keterpisahan itu berubah pertama kali ketika teknologi telegraf muncul, yang paling tidak membuat batasan waktu semakin bisa ditembus, meski segalanya masih dalam bentuk teks tertulis. Telegram digantikan kemudian oleh telepon yang membuat informasi yang tersampaikan tidak hanya teks tertulis, namun suara atau audio, meski masih bersifat person-to-person. Perkembangan lebih lanjut kemudian diikuti radio yang memungkinkan broadcast informasi sehingga seperti buku, informasi bisa tersampaikan ke orang banyak namun melalui suara.
Pada titik ini, kita mungkin perlu berhenti sejenak. Ingat sesuatu yang berkaitan dengan komunikasi berpusat pada pendengaran? Ya! Radio bersifat ‘mirip’ seperti bagaimana penyampaian informasi pada masyarakat bertradisi lisan. Suara dengan semua sifat yang dimilikinya yang membedakannya dengan teks visual, lahir kembali sebagai medium informasi saat Radio ditemukan. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa ini bukan berarti kelisanan juga terlahir kembali. Tidak sama sekali, kelisanan primer (kelisanan asli pada masa pra-literasi) telah punah sepunah-punahnya ketika alfabet tercipta (kecuali beberapa masyarakat yang saat itu masih belum tersentuh aksara sedikit pun). Orang yang menyiarkan radio tentunya berbasis pada teks, meskipun tidak secara literal, namun seminimal-minimalnya secara abstrak. Hampir mustahil pada masa ketika orang hidup bersama aksara, memberikan pidato tanpa berdasar pada teks yang paling tidak secara abstrak terbayang di pikirannya. Ini yang membuat Ong mengatakan bahwa literasi itu sesungguhnya seperti penjara, sekali dimasuki tidak dapat keluar darinya. Sekali orang mengenal aksara, ia tidak akan pernah bisa mengucapkan sesuatu tanpa membayangkan aksaranya. Jika tidak percaya, cobalah!
Orang bertradisi lisan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, berkomunikasi secara utuh. Ia menjadi pusat kosmos. Ia tidak hanya mengeluarkan informasi yang ada dalam pikirannya ke dalam bentuk suara, namun ia benar-benar menyampaikan seluruh pengalamannya (karena pikiran abstrak belum ada pada masyarakat literasi, pikiran adalah segala bentuk pengalaman) ke dalam seluruh tubuh fisiknya, tidak hanya suara. Hal ini yang kemudian dikenal sebagai verbomotorik. Informasi tersampaikan secara utuh melalui pandangannya, ekspresi mukanya, gestur tangannya, caranya berdiri, posisinya di kelompok, bahkan hingga hubungan sang pemberi informasi dengan yang menerima. Semua aspek itu, tidak tersampaikan oleh penyiar radio. Yang ada hanyalah suaranya saja, yang sudah terlepas dari pemberi suara. Orang yang mendengarkan radio tidak akan peduli pada siapa yang menyiarkan ataupun bagaimana ia menyiarkan, yang terpenting adalah informasi yang disampaikannya. Ini masih sangat khas literasi, bahwa yang mengetahui terpisah dari yang diketahui.
Revolusi teknologi tentu tidak berhenti pada transmisi audio via radio. Gambar visual pun kemudian menjadi aspek dari informasi yang di transmisikan dalam apa yang telah kita ketahui sebagai Televisi (TV). Bagaimana dengan Televisi? Ia mungkin bisa menambahkan beberapa aspek dalam komunikasi, seperti visual sang pembicara, yang menyangkut ekspresi wajah ataupun gestur, namun pemotongan visual ini tetap tidak mengembalikan lisan ke dalam bentuk yang seutuhnya. Kelisanan adalah tradisi yang rapuh. Sekali orang mengenal aksara, ia tak mungkin kembali ke tradisi lisan. Akan tetapi, kedekatan aspek yang dimunculkan TV dengan tradisi lisan membuat Ong kemudian menamakan ini sebagai kelisanan sekunder. Ia mirip seperti kelisanan, namun tidak sepenuhnya kelisanan. Ong mengatakan perbedaan jelas dari kelisanan primer dan sekunder adalah bahwa yang sekunder merupakan hasil dari kesengajaan, sedangkan yang primer hanya karena memang tidak ada alternatif lain.
Saya pribadi pada dasarnya tidak setuju jika TV atau radio dikatakan sebagai kelisanan sekunder. Aspek literasi pada TV dan radio masih mendominasi ketimbang aspek kelisananya. Terkait TV sendiri, meskipun ia telah secara lebih luas menampilkan tidak hanya suara, namun visual, informasi yang tersampaikan masih lah sekadar informasi yang terpotong dan tercerabut dari konteksnya. Penyiar berita di TV hanyalah perantara antara penerima informasi dengan pemilik informasi. Bukan ia lah yang memiliki otoritas terhadap informasi yang disampaikan, melainkan institusi yang berada di belakangnya. Kalaupun TV mencoba menampilkan beberapa potongan gambar realitas pun, mau bagaimanapun, itu semua tetaplah hanya potongan, bukan lah informasi utuh yang menyeluruh ketika kita murni berada dalam realitas tersebut.
Informasi yang kita terima dalam suatu momen sesungguhnya tidaklah terbatas pada gambar dan pendengaran. Seluruh sensor kita aktif setiap saat sehingga pengalaman sesungguhnya merupakan konsep holistik dari semua hal yang mengada di sekitar kita pada setiap waktu, mulai dari suhu udara, kelembapan, suasana, kecerahan, hingga suara-suara latar yang mungkin tidak kita sadari seperti kicauan burung atau gemerisik dedaunan. Semua itu hadir ketika masyarkat tradisi lisan berkomunikasi. Sedangkan, yang ditampilkan televisi hanyalah potongan realitas. Belum lagi, potongan realitas itu sifatnya intensional, artinya apa yang terlihat sesungguhnya tidak sekadar ‘terlihat’, tapi ‘diperlihatkan’. Hal ini akan membawa kita pada ranah yang lebih kompleks di bidang media studies, dan tulisan ini akan menjadi sebuah buku jika membahas sampai kesana. Dengan begitu, saya hanya ingin menekankan di sini bahwa TV sesungguhnya masih merupakan literasi dimana teks yang menjadi medium meluas dari hanya aksara menjadi audio dan visual. Ini yang kemudian saya sebut sebagai hiperteks.
Yang bisa kita tinjau kemudian adalah mengapa Ong mengatakan bahwa komunikasi berbasis hiperteks itu merupakan kelisanan sekunder. Ada dua hal yang menjadi dasar pendapatnya. Ong mengatakan bahwa TV dan radio menciptakan tribalitas, rasa seakan menjadi bagian dari kelompok, karena suara memusatkan pendengar dan dengan demikian memunculkan perasaan kelompok yang besar dengan sesama pendengar. Ini agak sedikit rancu bagi saya, karena justru TV menciptakan individualitas seperti halnya orang membaca buku. Kita menguasai medium informasi tersebut. Selayaknya orang bisa memilih untuk membaca buku sambil tidur, di toilet, atau dengan lambat, orang juga sesungguhnya bisa melakukan hal yang sama pada TV, apalagi di zaman yang lebih terkini dengan teknologi TV semakin canggih. Menonton TV pun bersifat reflektif dan personal ketimbang komunal, karena pengalaman menonton TV akan beda untuk setiap orang. Argumen Ong kedua, yakni bahwa TV mendukung spontanitas. Mungkin memang pada awal terciptanya TV, siaran ulang belum ada atau masih jarang terjadi, sehingga spontanitas informasi, sifat khas kelisanan, bisa muncul di situ. Akan tetapi, argumen ini pun sama patahnya ketika TV berkembang semakin canggih. Belum lagi revolusi teknologi telah membuat hiperteks tidak hanya berupa radio dan TV, namun semua multimedia yang bisa didapatkan dengan internet, yang tentu akan lebih kompleks lagi.
Menariknya, fenomena TV dan media visual, memunculkan dampak tersendiri, tapi bukan sebagai kelisanan sekunder, tapi sebagai pemberi informasi dimana penerima bersifat pasif. Ketika Donald Trump terpilih sekitar 2 tahun yang lalu, berbagai artikel dan komentar muncul di dunia maya yang mengatakan bahwa Trump adalah the first post-literate president. Mengapa? Sebagaimana dijelaskan dalam majalah New Republic, Trump sesungguhnya produk dari the age of television. Televisi, pada dasarnya membingkai realita, sehingga orang yang secara pasif hanya menonton TV, cakrawala mentalnya hanya terbatas pada layar itu. Trump adalah apa yang sering dilihat di TV, maka itulah realita yang orang-orang ketahui. Pembahasan lebih detail mengenai ini akan menyentuh media studies (lagi), jadi kita hentikan. Yang perlu dilihat kemudian adalah betapa kuatnya pengaruh TV dalam memberi efek samping pasifitas sehingga mengakibatkan terbingkainya paradigma orang.
Ketika orang memutuskan untuk menonton TV, maka ia akan duduk dan secara pasrah menerima apa yang terlihat di layar. Pilhan yang ia miliki hanya pada saluran yang ia tonton. Hal ini menarik, karena seperti apa yang saya jelaskan sebelumnya, TV masih bagian dari literasi, karena kita sesungguhnya (dan seharusnya) secara aktif menguasai medium informasi tersebut. Ketika kita membaca buku, kita tidak secara pasif begitu saja menerima apa yang diberikan oleh buku, tapi kita secara aktif berdialog dengan buku tersebut, melalui proses reflektif, imajinatif, dan interpretatif terhadap isi dari buku. Dalam pertelevisian, kita seakan memiliki pilihan, tapi sesungguhnya kita dibuat pasif.
Dalam interpretasi teknologi Don Ihde, bisa dikatakan TV telah menjadi ‘latar belakang’, dimana TV telah menjadi bagian dari ‘dunia’ di sekitar kita. Dalam acara keluarga misalkan, ketika kita pun hanya mengobrol, terkadang TV tetap dinyalakan sebagai latar belakang. TV bahkan sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan keseharian manusia. Orang melihat TV, maka ia melihat dunia. Hal ini mematikan daya pikir literasi yang telah dibangun berabad-abad sejak alfabet mulai diciptakan. Kita semakin tidak bisa reflektif, kritis, dan analitis terhadap dunia. Alih-alih, seperti kelisanan, kita menjadi reaksioner dan bersikap spontan akan apapun yang kita terima. Satu contoh sederhana diperlihatkan ketika awal-awal berkembangnya TV sebagai tren di Amerika Serikat digambarkan oleh Larry Gonick, penulis kartun komunikasi. Pada Oktober 1989 terjadi gempa di California Utara dan Gonick ada di lokasi saat gempa. Ia melihat bahwa kenyataannya hanya sedikit yang rusak, listrik nyala kembali dalam 5 jam, dan toko-toko buka esok harinya. Akan tetapi, jaringan TV menyiarkan tiga tayangan yang sama berulang kali: jalan layang yang runtuh, selain pemukiman yang porak proanda, dan satu jembatan yang rusak.
Dengan semua dampak yang ditimbulkan dari adanya TV, memang literasi seperti menemukan saingan. Secara ironis, saingan ini justru bersifat seperti kelisanan. Pada titik ini, barulah saya bisa sepakat bahwa pantas TV dikatakan sebagai kelisanan sekunder. Sayangnya, TV sesungguhnya hanya awal dari pengikisan besar-besaran dari literasi. Lebih dari itu, internet, bersama semua hiperteks yang disediakannya, berpotensi untuk merevolusi budaya, kebiasaan, dan cara berpikir orang hingga tahap yang mungkin bisa sama totalnya dengan revolusi literasi.
Kelisanan sekunder tidak berhenti pada efek reaksioner yang dihasilkan oleh TV. Karena untungnya, reaksi yang bisa diberikan terhadap TV masih bersifat terbatas. Orang yang jengkel dengan penyiar berita tidak bisa tiba-tiba membentak penyiar tersebut. TV masih bersifat satu arah, ia bukanlah kelisanan sekunder yang sempurna. Selain itu, TV masih berjarak dengan penonton TV, dalam artian, refleki kritis terhadap tontonan pun masih mungkin untuk dilakukan. Berita buruknya, kepincangan hiperteks ala TV disempurnakan oleh adanya internet yang memungkinkan komunikasi tanpa batas jarak, waktu, maupun media. Internet yang saya maksud di sini adalah media sosial beserta semua kapabilitasnya untuk menghubungkan semua manusia di bumi.
Dalam makalahnya, How the Secondary Orality of the Electronic Age Can Awaken Us to the Primary Orality of Antiquity, Robert M. Fowler menjelaskan beberapa ciri hiperteks yang bisa dilihat sebagai bentuk baru dari kelisanan. Ciri tersebut antara lain bahwa hiperteks melebur antara penulis dan pembaca. Dengan kata lain, siapapun bisa jadi pembaca sekaligus siapapun bisa jadi penulis, ditambah siapapun bisa menyebarkannya. Tidak ada otoritas yang bermain. Seseorang punya pikiran, maka ia bisa langsung menyampaikan itu ke semua orang tanpa melalui editor atau penerbit. Jika saya boleh menambahkan, mungkin isitilah yang pantas adalah pure anarchy. Mengenai istilah ini, Fowler memberikan ciri yang lain lagi namun dengan istilah yang lebih positif: dikatakan bahwa hiperteks bersifat “antihierarkis dan demokratis.”
Terkait itu, hiperteks sesungguhnya justru jadi lebih bersifat chaotic. Kita sekarang seakan berada dalam satu masyarakat global besar, dimana kita bisa berinteraksi secara bebas. Ini bisa diibaratkan seperti masyarakat lisan dahulu (dimana orang bisa berinteraksi secara langsung satu sama lain secara bebas), hanya lebih masif dan tak terbatas geografis. Bedanya lagi, masyarakat kelisanan primer dulu memiliki mekanisme kontrol dalam kelompoknya yang ditandai dengan adat istiadat, tata krama, dan sistem norma yang menjaga interaksi di antara mereka. Munculnya sistem norma tersebut dimungkinkan karena masyarakat kelisanan primer masih terbilang cukup kecil dan belum kompleks. Sistem norma ini menjaga ikatan dan keteraturan dalam kelompok, meskipun mungkin pada beberapa kasus, telah terdapat adanya otoritas hirarkis yang menaungi. Intinya, ada semacam otoritas yang mengontrol interaksi masyarakat. Dalam kondisi ketika otoritas itu nyaris tidak ada karena sifat antihierarkis hiperteks, reaksi yang dihasilkan kelisanan sekunder dalam era hiperteks tidak akan terkontrol, sehingga cenderung bersifat disruptif ketimbang demoktratis. Hal ini ditambah dengan mental virtual (baca: Dalam Penjara Teknologi) yang membuat orang merasa ‘aman’ dengan adanya keberjarakan akan dirinya dengan masyarakat lain. Orang akan lebih berani mengungkapkan egonya di dunia maya dengan adanya mental virutal ini, yang jelas-jelas tidak akan berani dilakukan secara langsung. Ambil lah satu sesi komentar dalam suatu video di youtube atau suatu status di facebook, meskipun tertulis, mereka seakan tengah berinteraksi secara lisan dengan ekspresi yang lebih berani, meskipun tidak total.
Efek disrupsi ini sesungguhnya bisa menjadi sangat negatif bila diamati lebih seksama. Muncul kembalinya aspek-aspek kelisanan melahirkan kembali juga sifat tribalitas. Interkoneksi global yang terjadi membuat interaksi antar kelompok dengan berbagai label semakin jelas dan lepas, sehingga orang memiliki label suatu kelompok tidak akan merasa sebagai “aku” di dunia maya, tapi merasa sebagai “kelompok A”, atau “kelompok B.” Dampak buruknya adalah, friksi antar kelompok jadi sangat mudah terjadi. Ini kemudian diperparah lagi oleh mentalitas virtual dan daya reaksioner dari kelisanan sekunder ala hiperteks dan interkoneksi internet.
Seberapa miripnya semua fenomena di internet itu dengan kelisanan, mau tidak mau, informasi yang tersampaikan via internet pada titik sekarang ini (entah di masa depan) masilah merupakan potongan dari realitas. Kita hanya bisa berinteraksi melalui suara yang dituliskan, alias chat, melalui suara sungguhan (voice call), atau melalui suara plus visual dari lawan bicara (video call). Interaksi ini, memang seperti mengaktivasi hampir semua aspek kelisanan, kecuali keutuhan dan kemenyeluruhannya. Sayangnya, keutuhan dan kemenyuluruhan merupakan aspek penting dalam kelisanan yang sangat kontras dengan cara pikir literasi yang begitu analitis dan terpisah-pisah. Kondisi ini, kondisi dimana literasi seakan memunculkan kecenderungan untuk ‘kembali’ ke kelisanan namun dalam bentuk yang lebih baru, yang mungkin pantas kita namakan pasca-literasi.
Dough Johnson, seorang pengajar dan pengamat teknologi, dalam sebuah artikel berpendapat hal serupa terkait era hiperteks ini. Ia mengatakan “but I would argue that post literacy is a return to more natural forms of multisensory communication—speaking, storytelling, dialogue, debate, and dramatization. It is just now that these modes can be captured and stored digitally as easily as writing. Information, emotion, and persuasion may be even more powerfully conveyed in multimedia formats.” Kita seakan return, kembali, ke masa kelisanan, masa dimana komunikasi bersifat multisensory. Fowler bahkan menyebut era hiperteks ini sebagai Back to the Future, mengikuti judul sebuah film mengenai perjalanan lintas waktu. Pasca-Literasi seakan mengambil kembali aspek-aspek kelisanan, seperti emosi, persuasi, dan verbomotorik.
Apakah ini buruk? Akan menjadi seperti apa kelak fenomena ini di masa depan? Dan, Bagaimana menyikapinya? Semua pertanyaan itu bukanlah hal yang mudah untuk dijawab, karena semua relatif bergantung bagaimana kita melihat fenomena ini.
Melampaui Masa Depan
Fenomena terkikisnya literasi dalam berbagai segi, baik dari ranah praksis di wilayah penerbitan, kepenulisan, dan perbukuan, hingga ke ranah abstrak di wilayah kebiasaan, budaya, paradigma, dan pola pikir, bisa dikatakan berakar dari kecenderungan kembali ke ‘kelisanan’. Jika begitu, pertanyaannya pun berganti menjadi, apa sesungguhnya yang menyebabkan kecenderungan itu? Apakah semua murni dari perkembangan teknologi? Saya rasa mengingat pembahasan mengenai literasi sangat menyangkut dengan manusia, maka jawabannya mungkin tidak akan sesederhana itu. Secara makroskopis tentu banyak faktor yang mempengaruhi, yang mungkin bisa jadi bahan analisis lebih lanjut (tidak dalam tulisan ini tentunya). Untuk kali ini, saya akan lebih mencoba mendekatinya dari sisi abstrak-holistik.
Jika kita lihat dalam kacamata kosmos, sesungguhnya yang tejadi pada manusia ini bisa dikatakan anomali, paling tidak untuk hukum termodinamika kedua. Hukum itu mengatakan bahwa semesta akan selalu memiliki kecenderungan untuk mengarah pada kompleksitas yang lebih rendah. Hampir seluruh ruang jagad raya ini hanyalah ruang kosong yang gelap. Bintang hanya ada pada beberapa titik, yang dibandingkan dengan ruang kosongnya jelas tak seberapa. Bintang itu sendiri akan menua dan mati, hingga akhirnya kompleksitas pun terus berkurang. Akan tetapi, melihat sistem tata surya, kemudian zoom in ke Bumi. Hukum itu seakan tidak berlaku! Kenyataannya, peradaban manusia merupakan salah satu bukti bagian dari semesta dimana justru kompleksitas semakin meningkat.
Fenomena increasing complexity ini, oleh David Christian, dalam proyeknya The Big History Project, dijelaskan dalam 8 tahap treshold dengan Goldilock condition-nya masing-masing, yang secara ‘beruntung’ kita lewati sehingga bisa terus mengaktifkan emergent properties dan menciptakan kompleksitas baru. Kondisi Goldilocks sendiri merupakan kondisi yang just right, tidak lebih, tidak kurang, sehingga memungkinkan munculnya kompleksitas yang lebih tinggi. Contoh dari kondisi Goldilocks adalah jarak Bumi ke matahari. Lebih dekat sedikit, air akan menguap, dan lebih jauh sedikit, air akan membeku. Jarak bumi ke matahari merupakan jarak yang tepat untuk mejaga air dalam fase cairnya dan menghasilkan kehidupan. Sedangkan emergent properties atau sifat kemunculan, merupkan sifat universal yang memungkinkan suatu sistem kompleks untuk memunculkan sifat baru dan unik dalam suatu kondisi tertentu apabila dilihat secara utuh. Salah satu contoh sifat kemunculan ini adalah sel organisme. Setiap komponen dari sel hanyalah zat kimia mati, tetapi dalam satu keutuhan sel, dengan kondisi yang tepat, sistem kompleks zat kimia penyusun sel memunculkan sifat baru yang menjadikan sel itu hidup.
Mengapa tiba-tiba membahas ini? Karena dalam narasi besar semesta, salah satu dari treshold yang kita lalui adalah terciptanya sistem agrikultur yang memungkinkan masyarakat untuk menciptakan peradaban yang lebih kompleks, dan dengannya memunculkan aksara. Aksara sendiri kemudian sangat memungkinkan peningkatan kompleksitas yang terjadi semakin drastis dan cepat. Berkembangnya aksara dan kemudian literasi memicu threshold terakhir yang dilalui umat manusia untuk kembali mengakselerasi peningkatan kompleksitasnya, yakni revolusi modern yang dimulai sekitar 200 tahun yang lalu, ketika revolusi industri mulai tumbuh dan otomisasi mesin menapaki kelahirannya. Semua threshold ini memungkinkan kita untuk melampaui, melanggar, dan menembus hukum termodinamika kedua, dan menciptakan peradaban yang kita alami pada detik ini. Tapi, apakah tanpa cost sedikitpun? Tentu tidak. Perhatikan dalam kompleksitas yang kecil tumbuh di bumi ini, di tempat lain semesta kompleksitas tetap akan terus berkurang. Dengan kerumitan kehidupan manusia di Bumi, jagad raya tetap lah hanya berupa ruang kosong. Increasing complexity hanya terjadi secara terpusat, dan bahkan melingkupi ranah yang semakin sempit. Pada masyarakat kelisanan primer dulu, pengetahuan tidak memiliki kesenjangan antar setiap manusia. Semua orang memiliki kemungkinan akses terhadap pengetahuan yang sama. Ketika literasi berkembang, pengetahuan menciptakan kesenjangan antara yang lebih mengetahui dengan yang tidak, apalagi ketika pengetahuan itu semakin kompleks dan detail. Pada zaman sekarang, masyarakat hanya tahu menggunakan internet, smartphone, dan berbagai teknologi lainnya, namun sama sekali buta atas apa yang ada di baliknya. Dengan semakin rumitnya pengetahuan, yang bisa mengetahui semua pengetahuan itu semakin sedikit. Informasi semakin kompleks, namun semakin memusat. Pada akhirnya, general entropy is always increasing!
Sedikit mengenai entropi, terdapat sebuah konsep yang dinamakan entropi informasi. Ia mirip dengan entropi kalor, namun dalam ranah yang berbeda. Tentu penggunaan istilah entropi informasi yang digunakan Claude Shannon dalam teori informasi berbeda dari yang saya maksud. Di sini saya hanya mengadopsi istilah mengingat konteksnya akan lebih jelas dengannya. Kalor/energi merupakan unsur ekstrinsik dari sesuatu. Bersama materi, ia menyusun dunia fisik kita ini. Oleh Fritjof Capra, dua hal ini (materi dan energi) digeneralisasi menjadi struktur dan proses, yang secara inheren akan selalu menjadi unsur ekstrinsik segala hal, termasuk organisasi masyarakat. Akan tetapi, ada unsur intrinsik di balik itu yang sering dilupakan para materialis. Segala sesuatu, menyimpan ‘informasi’ di dalamnya, yang apabila dikomparasi dengan aspek ekstrinsik, bisa dianalogikan dengan kalor. Ia, juga, dengan demikian memiliki hukum ‘termodinamika’ juga, yakni bahwa informasi akan selalu tersebar dengan kompleksitas yang menurun. Informasi ini bermacam-macam, bisa berupa konfigurasi elektron yang mendefinisikan suatu unsur, DNA yang mendefinisikan ciri makhluk hidup, hingga pengetahuan kompleks manusia. Jika kita lihat dengan seksama sejarah besar semesta, kita akan lihat bagaimana hukum ‘termodinamika’ informasi, bersama dengan sifat kemunculan, memusatkan kompleksitas pada ranah yang semakin sempit, namun secara menurunkan kompleksitas secara general.
Jika pusing, mari kita coba ke wilayah dengan abstraksi lebih minim. Saya katakan sebelumnya bahwa literasi mendorong modernisme untuk lahir dan berkembang. Perkembangan modernisme ini, setelah melewati masa kejayaannya, ternyata justru menimbulkan banyak polemik di berbagai bidang. Salah satu dari polemik itu tentu saja teknologi, sebagaimana telah saya bahas. Beberapa polemik itu memicu gerakan di hampir segala keilmuan untuk melakukan refleksi kritis terhadap modernisme. Gerakan ini yang kemudian sering dinamakan dengan posmodernisme. Beberapa polemik yang menjadi raisson d’etre gerakan posmodernisme dipaparkan oleh Bambang Sugiharto dalam Posmodernisme: Tantangan bagi Filsafat antara lain sebagai berikut. Pertama, pandangan dualistik modernisme mengakibatkan objektivisasi dan eksploitasi alam secara berlebihan, hingga kemudian memicu krisis ekologi. Kedua, pandangan modern yang bersifat objektivistis dan positvistis akhirnya cenderung menjadikan manusia seolah objek juga, dan masyarakat pun direkayasa bagai mesin, sehingga menjadi kurang manusiawi. Ketiga, dalam modernisme ilmu-ilmu positif-empiris mau tak mau menjadi standar kebenaran tertinggi, hingga nilai-nilai moral dan religius kehilangan wibawanya dan akhirnya menimbulkan disorientasi moral-religius. Keempat, suburnya materialisme, yang menganggap materi adalah kenyataan terdasar, dengan aturan main utama survival of the fittest. Kelima, milterisme, disebabkan oleh norma moral-religius, plus norma umum objektif semakin tidak berlaku, maka satu-satunya cara mengatur manusia adalah dengan kekerasan (Untuk ini, saya kurang setuju sebenarnya). Keenam, seperti yang telah saya bahas sebelumnya, bangkitnya kembali tribalisme, atau mentalitas yang mengunggulkan kelompok sendiri.
Dari paparan beberapa polemik modernisme di atas, semuanya mengarah pada terjadinya efek balik kompleksitas secara general. Krisis ekologi jelas menghancurkan kompleksitas yang telah alam bentuk selama jutaan tahun. Objektivisasi manusia, ditambah runtuhnya nilai moral-religius, yang digantikan imperialisme sains dan menyuburkan materialisme, menghancurkan kompleksitas kemanusiaan yang juga telah terbentuk selama ribuan tahun. Terakhir, tribalisme membuat yang objektif itu sendiri runtuh, dan kita kembali pada masa dimana subyektivitas kelompok yang menjadi utama. Secara umum, kita seakan mengalami penurunan kompleksitas. Tapi faktanya, pada sisi lain dunia, sekelompok orang masih terus meningkatkan kompleksitas dengan berbagai penelitian terhadap artificial intelligence, astrofisika, neurosains, dan lain sebagainya. Akan tetapi, semua pengetahuan itu, semakin menciptakan gap yang sangat besar dengan pengguna dan masyarakat awam pada umumnya. Pengetahuan terasingkan dan terelitisasi hanya oleh beberapa orang. Kompleksitas meningkat tapi memusat, di sisi lain secara general kompleksitas di tempat lain pada dasarnya menurun.
Apa artinya semua itu? Jika semua pemaparan saya di atas benar, maka kita hanya punya 4 pilihan. Dari 4 pilihan itu, 3 di antaranya saya adopsi dari pengelompokan gerakan posmodernisme yang dipaparkan Sugiharto. Pilihan pertama, kita bisa memang secara sengaja kembali ke pola berpikir pra-modern atau pra-literasi, namun mengamplifikasi dan mengoptimalkannya sehingga kita bisa mentransendensi diri untuk menjadi lebih holistik. Kita bisa menjadi manusia utuh yang merupakan hibrida pola pikir rasionalisme literasi dengan kebijaksanaan kelisanan. Banyak pemikir yang telah mengarah ke sana, salah satunya adalah fisikawan yang saya telah sebutkan sebelumnya, yakni Fritjof Capra. Ia mencoba menggabungkan konsep fisika kuantum dengan mistisme timur. Dalam hal ini, literasi akan memang sengaja ditinggalkan, untuk kemudian lebih mencari sumber pengetahuan lain yang lebih esoteris dan mistis melalui pengalaman spiritual. Mungkin, slogan yang tepat untuk pilihan ini adalah apa yang sering saya ungkapkan juga pada beberapa tulisan saya: Berhentilah membaca, berlatihlah praktik, berupayalah mengalami.
Pilihan kedua merupakan ekstrim yang berlawanan dari yang pertama, yakni memilih untuk secara total menggeluti modernisme, kemajuan teknologi, dan neo-literasi yang berkembang bersamanya. Belajarlah machine learning, pelajari semua aspek teknologi, geluti big data, pahami sistem kerja internet, maksimalkan pembelajaran via online course. Orang yang berada di pilihan ini memang memilih untuk berlari bersama arus ketimbang secara skeptis menolak atau mempertanyakannya. Kemajuan teknologi sudah ada di depan mata. Either run or left behind. Semua efek samping, permasalahan etis, dan dampak sosio-ekologis yang muncul dari teknologi hanyalah konsekuensi dari sifat manusia, dan kita bisa memberikan solusi dari semua permasalahan itu dengan teknologi yang lebih baru dan lebih canggih.
Daripada berada di salah satu kutub ekstrim, mungkin akan lebih baik untuk menciptakan dialog dan menjembatani keduanya. Itulah yang menjadi pilihan kita yang ketiga. Wilayah ini cukup jarang diisi. Karena dari pengamatan kasar saya, selalu terlihat dua kelompok orang. Mereka yang bergelut di ranah filosofis dan memberikan kritik terhadap kemajuan teknologi, namun tidak memahami apa-apa terkait apa yang ada di dalam teknologi itu sendiri, atau mereka yang bergelut di ranah teknis, memahami seluk-beluk teknologi, namun tidak pernah merefleksi apa-apa terkait perkembangan teknologi itu sendiri. Tentu ada kelompok orang lain lagi, yang justru merupakan kelompok mayoritas, yang akan saya paparkan sebagai pilihan keempat setelah ini. Memilih untuk berada di tengah dan menjembatani dua kutub bukanlah hal yang mudah. Kita harus secara total mempelajari dua ranah sekaligus, ranah filosofis dan ranah teknis. Hal ini bukan berarti tidak mungkin, terutama untuk yang masih muda dan lebih akrab dengan teknologi. Pada pilihan ini, muncul istilah transliterasi sebagai jawaban sementara atas solusi permasalahan yang muncul dari fenomena pasca-literasi. Transliterasi merupakan generalisasi literasi sebagai pembacaan lintas media dan bersifat kontekstual. Transliterasi berusaha berdialog secara lebih kritis terhadap arus informasi yang muncul tak terkendali.
Pilihan keempat, pilihan yang tidak saya rekomendasikan, adalah mendekonstruksi habis literasi hingga pada titik ekstrimnya berujung pada nihilisme. Dekonstruksi ini sesungguhnya telah terjadi secara tak sadar dengan ‘pasrah’ dan pasifnya kita pada media sosial, TV, dan teknologi pembunuh literasi lainnya. Ironisnya, justru pilihan ini adalah pilihan yang dipilih mayoritas orang. Membaca buku adalah nihil bila kita bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan secara lebih praktis melalui Youtube atau artikel singkat di berbagai blog. Cukup puaslah dengan informasi yang berseliweran melalui whatsapp, LINE, telegram, instagram, dan nikmati hidup ini apa adanya. Mau seperti ini? Itu pilihan. Saya tidak mengatakan ini buruk karena keadaan itu sudah berada di depan mata untuk bisa dihindari. Dalam pandangan pesimis saya, fenomena yang terjadi seperti itu sudah merupakan efek natural dari adanya teknologi (penjelasan lebih detail, baca booklet Te(kn)ologi saya). Saya hanya tidak merekomendasikannya.
Bila dirangkum, pilihan pertama bisa disebut konservatif, pilihan kedua bisa disebut agresif, pilihan ketiga bisa disebut moderat, dan pilihan keempat bisa disebut pasif. Semua ini tentu adalah pilihan. Apa yang terjadi di masa depan bergantung dari dinamika 4 pilihan ini, sehingga masih terbuka beragam kemungkinan akan apa yang terjadi kelak. Bila kita pesimis, mungkin pilihan ke-2 dan ke-4 akan dominan dan lahirlah dunia seperti film The Matrix. Bila mau agak sedikit optimis, mungkin pilihan ke-2 dan ke-3 yang dominan dan apa yang terjadi di film Transendence bisa terjadi. Analisis detail mengenai dinamika keempat pilihan ini dan semua kemungkinan masa depan yang dibentuknya mungkin bisa dilakukan lebih lanjut di tulisan lain. Akan tetapi, sampai titik ini, saya hanya ingin menjelaskan bahwa pasca-literasi masihlah merupakan blackbox, era gelap di masa depan yang masih belum bisa kita pastikan seperti apa. Threshold selanjutnya untuk mengakselerasi peningkatan kompleksitas masih mungkin untuk dilalui, tentu dengan cost effect yang saya jelaskan di atas.
Yang bisa saya pastikan di sini adalah apa yang Michael Ridley katakan, bahwa literasi baca-tulis ala aksara tidak akan bertahan. Kecuali kelak tiba-tiba internet mendadak hancur atau semua perangkat elektronik mendadak mati, literasi akan berevolusi ke bentuk yang baru, sebuah neo-literasi. Hiperteks akan terus berkembang hingga kelak bahkan memungkinkan transfer informasi bisa melalui apa yang disebut techlepathy, atau kehidupan ini menjadi murni simulasi dalam virtual reality. Bentuknya seperti apa, kita tidak bisa memastikan, karena semua ada pada pilihan kita yang hidup sekarang. Dengan semua itu, mengutip kembali Ridley, cukup mari kita rayakan:
“Reading and writing are doomed. Literacy as we know it is over. Welcome to the post-literate future.”
(PHX)
Referensi
[1] Ong, Walter J. 2013. Kelisanan dan Keaksaraan. Yogyakarta: Penerbit Gading.
[2] Sugiharto, Bambang. 1996. Postmodernisme: Tantangan Bagi Filsafat. Yogyakarta: Kanisius.
[3] Ridley, Michael. 2012. Beyond Literacy [online] (http://www.beyondliteracy.com/), diakses tanggal 20 Januari 2018.
[4] Diamond, Jared. 2013. Guns, Germs, & Steel: Rangkuman Riwayat Masyarakat Manusia. Jakarta: KPG.
[5] Dawami, M Iqbal. 2017. Pseudo Literasi. Surabaya: Maghza Pustaka.
[6] Gonick, Larry. 2007. Kartun (Non) Komunikasi. Jakarta: KPG.
[7] Gong, Gol A; Irkham, Agus M. 2012. Gempa Literasi. Jakarta: KPG.
[8] Fowler, Robert M. 1994. How the Secondary Orality of the Electronic Age Can Awaken Us to the Primary Orality of Antiquity or What Hypertext Can Teach Us About The Bible. Interpersonal Computing and Technology: An Electronic Journal for the 21st Century, Vol.2 2, No. 3, p.12-46.
[9] Christian, David. 2011. The history of our world in 18 minutes [video file] (https://www.ted.com/talks/david_christian_big_history/). Diakses tanggal 3 November 2017.
[10] Lim, Francis. 2008. Filsafat Teknologi: Don Ihde tentang Manusia dan Alat. Yogyakarta: Kanisius.
[11] Capra, Fritjof. 2000. Tao of Physics: Menyingkap Pararelisme Fisika Modern dan Mistisme Timur. Yogyakarta: Jalasutra.
[12] Ihsan, Aditya F. 2016. Booklet Phx #15: Te(kn)ologi [online], (https://issuu.com/aditya-finiarelphoenix/docs/_15_te_kn_ologi), diakses tanggal 5 Juni 2017.
[13] Bertonneau, Thomas F. 2014. Post-literacy and Refusal to Read [online], (https://orthosphere.wordpress.com/2014/01/08/post-literacy-and-the-refusal-to-read/), diakses tanggal 20 Januari 2018.
[14] Heer, Jeet. 2017. The Post-Literate American Presidency [online], (https://newrepublic.com/article/144940/trump-tv-post-literate-american-presidency), diakses tanggal 20 Januari 2018.