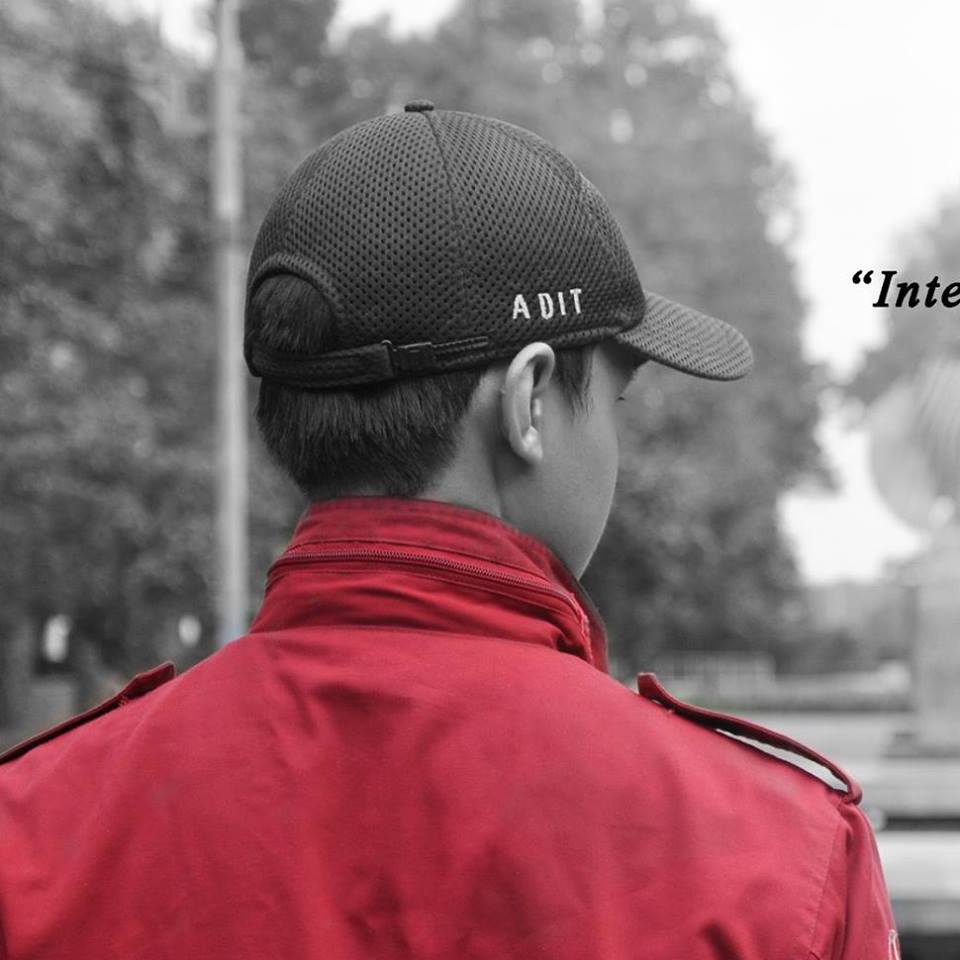Literasi Mencari Arti
- 21 mins“Sebenarnya dalam sejarah peradaban umat manusia, kemajuan suatu bangsa tidak bisa dibangun dengan hanya bermodalkan kekayaan alam yang melimpah maupun pengelolaan tata negara yang mapan, melainkan berawal dari peradaban buku atau penguasaan literasi yang berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya.”
-– Anonim –-
Baca dan tulis sudah menjadi tindakan yang secara wajar terjadi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari yang sesederhana membaca papan reklame di sepanjang jalan, atau menuliskan nama sendiri ketika mengisi suatu formulir tertentu. Mungkin bisa dikatakan lebih dari setengah waktu kita dalam sehari selain tidur dihabiskan dengan dua tindakan tersebut. Tentu, dua tindakan itu bukan lah hal yang aneh. Justru yang aneh adalah apabila tidak bisa melakukan dua tindakan itu. Sayangnya, betapa biasanya dua tindakan itu justru seakan menenggelamkan makna sesungguhnya dan apa kekuatan di baliknya.
Baca dan tulis sering dikaitkan dengan satu kata yang mungkin masih tidak terlalu terbiasa pada kebanyakan orang. Ya, literasi. Istilah ini banyak disebut-sebut di dunia akademis, di dunia kepustakaan, dan juga dunia keaksaraan, serta pada beberapa tempat lainnya. Sering dikatakan juga bahwa budaya literasi adalah hal yang paling penting dalam membangun peradaban. Anehnya, dengan semua teori atau teks lain yang berkata banyak mengenai literasi, kata ini bahkan tidak tercantum dalam KBBI edisi IV, yang mana hanya mengandung dua kata ubahannya, yaitu aliterasi dan transliterasi. Lantas apa sebenarnya literasi?
Dunia Teks
Karena kamus utama pembendaharaan kata Bahasa Indonesia edisi terbaru sendiri tidak mencantumkan definisi literasi, maka mungkin kita perlu melihat istilah ini secara etimologis. Jika ditarik mundur, literasi merupakan adopsi dari bahasa inggris literacy, yang secara sederhana bisa diartikan sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis. Saudara-saudaranya, literate, literature, literary, dan juga letter, berasal dari akar yang sama, yakni bahasa yunani littera yang berarti teks atau tulisan beserta sistem yang menyertainya. Istilah ini kemudian berkembang ke bahasa-bahasa lain di Eropa sekitar abad pertengahan hingga akhirnya diartikan secara umum sebagai hal-hal terkait baca dan tulis.
Dewasa ini, istilah literasi sendiri sudah sangat diperluas menjadi kemampuan menganalisa dan juga menghitung. Pengertian literasi bahkan bertransformasi lebih luas lagi sehingga memunculkan istilah-istilah seperti literasi media, literasi komputer, literasi politik, dan lain sebagainya. Penggunaan terminologi-terminologi ini memang hanya terpakai pada kalangan tertenu saja secara khusus untuk tujuan akademis atau pembahasan tertentu. Walaupun pengertian literasi sendiri sudah meluas dan menciptakan ragam persepektif yang berbeda-beda, namun pada dasarnya ia memiliki inti makna yang sama.
Beberapa pakar sudah sering mengungkap mengenai definisi literasi berdasarkan sudut pandang masing-masing. Salah satunya adalah yang dinyatakan oleh Niko Besnier yang mengatakan “literasi adalah komunikasi melalui inskripsi yang terbaca secara visual, bukan melalui saluran pendengaran dan isyarat. Inskripsi visual di sini termasuk di dalamnya adalah bahasa tulisan yang dimediasi dengan alfabet, aksara.”. Pengungkapan lain dinyatakan oleh Richard Kern, yang mana mengatakan, “Literasi adalah penggunaan praktik-praktik situasi sosial, dan historis, serta kultural dalam menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks.”
Lain lagi yang dinyatakan oleh Irwin Krisch dan Ann Junglebut yang mendefinisikan literasi dalam konteks kontemporer yang mana merupakan “kemampuan seseorang dalam menggunakan informasi tertulis atau cetak untuk mengembangkan pengetahuan sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat.” Terakhir, melihat UNESCO, lembaga internasional di bidang pendidikan dan budaya itu mendefinisikan literasi sebagai “kemampuan mengidentifikasi, memahami, menginterpretasi, mencipta, berkomunikasi, dan menghitung, menggunakan material tertulis dan tercetak yang terkait dengan beragam konteks.”
Dari semua definisi itu, mungkin lebih baik jika melihat benang merahnya dari asal mula konteksnya. Pada awalnya literasi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan teks. Pengertian teks dalam hal ini bisa dinyatakan sebagai objek material yang memiliki informasi atau makna yang bisa diambil oleh subjek melalui perantara atau cara tertentu, atau dengan kata lain, teks adalah pembawa informasi. Teks pada awalnya tentu hanya merupakan tulisan di atas kertas atau media lain yang berisi informasi berupa rangkaian torehan tinta berbentuk aksara untuk kemudian diinterpretasikan. Di sini arti dasar menulis dan membaca muncul, yang mana menulis merupakan proses penorehan informasi dan mencipta teks tersebut, dan membaca merupakan proses menginterpretasikan dan menafsir teks dengan mengekstrak informasi yang tertoreh.
Teks sendiri tidak sekedar asal dibaca dan ditulis, karena proses menulis atau membaca itu sendiri merupakan kegiatan yang bertingkat. Peter Freebody dan Alan Luke pada 1999 mencetuskan model literasi (dikenal sebagai Four Resource Model) yang menjelaskan bagaimana interaksi antar manusia dengan teks terjadi. Interaksi ini terangkum dalam 4 aktivitas, yakni memahami konteks, mencipta makna, menggunakan teks secara pragmatis, dan melakukan analisis dan transformasi teks.. Keempatnya merentang dari menarik informasi mentah berdasarkan konteks hingga membedah informasi tersebut untuk diinterpretasikan lebih dalam. Sebagai pembawa informasi, berbicara mengenai teks akan menyinggung mengenai sistem yang ada dalam teks itu sendiri, seperti bagaimana informasi itu terekam dan makan apa yang terkandung di dalamnya.
Dalam hal ini, teks menghubungkan dua subjek berbeda, antara penulis dan pembaca, dengan media aksara. Aksara sendiri merupakan sistem simbol yang bisa digunakan untuk membawa informasi dan menjadi media komunikasi. Aksara secara kompleks menciptakan rangkaian tata aturan, dari semiotika, sastra, sintaks, semantik, hingga morfologi, yang mana terangkum dalam kesatuan utuh sistem bahasa. Karena itulah berbicara mengenai literasi sesungguhnya berbicara mengenai kebahasaan, karena bagaimana teks itu menyimpan makna melalui sistem bahasa atau linguistik. Itulah sebenarnya yang sejak Sekolah Dasar diajarkan pada anak-anak sekolah sebagai pelajaran “Bahasa Indonesia” sesungguhnya adalah kemampuan literasi.
Antara Tulisan dan Lisan
Teks, bila diperluas, sebenarnya bukan lagi hanya kumpulan aksara tertulis ataupun virtual yang terbaca secara visual, namun bisa mencakup segala sesuatu yang menyimpan makna, termasuk audio. Dari suara manusia, rangkaian peristiwa, hingga alam semesta ini bisa dianggap sebagai teks yang bisa dibaca, sebagaimana diperintahkan juga dalam agama Islam untuk Iqra yang mana dalam arti luasnya adalah membaca makna-makna yang terkandung di alam. Tentu saja sistem bahasa yang dipakai tidak hanya sekedar aksara alfabet yang biasa digunakan manusia, namun beragam aspek yang berbeda-beda tergantung teks yang terbaca. Maka bila memakai arti teks secara luas ini, literasi menjadi tidak sekedar melulu mengenai tulisan, namun bisa mencakup segala sesuatu yang terkait dengan penciptaan dan interpretasi makna. Dari sinilah muncul istilah-istilah seperti literasi politik, yang mana merupakan kemampuan membaca keadaan politik, literasi media, kemampuan membaca media, dan literasi-literasi lainnya. Walaupun pemaknaannya bisa seluas itu, ada suatu ciri khas literasi yang menjadi poin utama mengapa literasi adalah hal yang penting dalam peradaban.
Mengenai hal ini, perlu dilihat bahwa dalam sistem pertukaran atau penyampaian informasi, terdapat dua pembagian tradisi yang kontras menjadi corak individu, kelompok, atau masyarakat. Dua tradisi ini adalah tradisi tulisan, yang juga sering disebut tradisi literasi, dan tradisi lisan. Pada awalnya, kedua tradisi ini hanya didefinisikan berdasarkan media atau perantara informasi yang digunakan, yang mana pada tradisi tulisan, informasi tersampaikan secara visual melalui teks tertulis, sedangkan pada tradisi lisan, informasi tersampaikan secara audio melalui interaksi langsung. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung pada corak kultural masyarakatnya. Dikotomi ini tidak menjadi masalah hingga teknologi bernama Radio dan Televisi ditemukan.
Ketika radio dan televisi muncul dan mewarnai kehidupan bermasyarakat, ia menciptakan kultur yang ambigu antara lisan dan tulisan. Apalagi ketika kemudian teknologi informasi terus berkembang dan memunculkan media lain seperti SMS (short message service), chat, dan semacamnya. Ambiguitas ini yang kemudian membuat dikotomi tulisan dan lisan perlu diperluas hingga bukan lagi sekedar mengenai perantara informasi yang digunakan, tapi lebih bagaimana interaksi yang tercipta antara pengguna dengan informasi itu sendiri.
Tradisi tulisan cenderung menciptakan ruang eksklusif yang mana tercipta dialog kritis antara pengguna dan informasi (dalam teks berbentuk apapun). Ciri khasnya adalah adanya ruang dan waktu khusus untuk mengupas informasi dari teks sesuai dengan konteks dan makna yang dimunculkan oleh pengguna. Contoh sederhana adalah ketika kita membaca buku, kita seakan tenggelam dalam informasi-informasi buku tersebut, menciptakan dialog intim dan intens antara pikiran kita dengan teks, yang mana kita bisa bebas mengimajinasikan dan menginterpretasikan semuanya sebebas mungkin. Hal inisesuai dengan model literasi (four resource model) yang dicetuskan Luke & Freebody. Sedangkan pada tradisi lisan, ruang itu bersifat inklusif sehingga pemaknaan yang muncul akan berupa konvensi atau kesepahaman antar dua atau lebih individu. Secara sederhana, tradisi lisan membuka ruang tanggapan multi arah, ketika pada tradisi tulisan tidak. Dalam tradisi lisan, setiap individu adalah teks yang mana terbaca melalui komunikasi yang tercipta. Karena dalam tradisi lisan tidak ada teks dalam bentuk material yang lain, maka memori menjadi kekuatan utama tradisi lisan. Sekalinya seseorang lupa atau pemilik informasinya meninggal dunia, maka teks itu akan hilang selamanya. Secara singkat, bisa dikatakan bahwa tradisi lisan mengandalkan kemampuan memori dan komunikasi, dan tradisi tulisan mengandalkan kemampuan analisis dan interpretasi.
Indonesia pada umumnya merupakan masyarakat bertradisi lisan. Walau pada beberapa tempat sempat ditemukan beberapa bukti lain bahwa tulisan juga sempat mewarnai kebudayaan Indonesia, namun bila dilihat lebih general, ciri khas tradisi lisan menjadi hal yang paling menonjol. Hal ini terlihat dari bagaimana pengetahuan atau wawasan kebudayaan cenderung selalu tersampaikan turun temurun melalui cerita-cerita dan obrolan, bukan melalui teks tertulis. Selain itu, adat-adat atau tata krama yang tercipta dalam suatu kebudayaan masyarakat hanya terjaga melalui rutinitas kehidupan sehari-hari dan tidak pernah tertulis. Ini bukanlah hal yang buruk tentunya, tradisi lisan memiliki kelebihannya sendiri. Namun sayangnya, ketika Belanda masuk Indonesia, masyarakat kolonial membawa tradisi tulisan atau literasi dari peradaban Eropa, membuat adanya transisi tradisi di Indonesia. Ketika Indonesia tidak siap, yang ada akhirnya adalah ketidakjelasan kultural, sebagaimana terjadi hingga saat ini. Kita merasa sudah menjadi masyarakat literasi, namun secara kebiasaan dan sifat dasar, masih terbawa tradisi lisan. Akhirnya, bisa menulis ya enggak, memori kuat ya juga enggak. Salah satu contoh sederhana adalah bagaimana kita lebih mementingkan kebiasaan umum ketimbang hukum tertulis, dari aturan lalu lintas hingga aturan birokrasi.
Bias Teknologi
Seperti halnya dikotomi lainnya, menjadi ekstrim hanya di satu sisi bukanlah hal yang baik. Terlalu lisan akan membuat informasi tidak terjaga dengan baik dan tidak adanya pengembangan gagasan dari analisis teks yang hanya ada dalam tradisi literasi, sedangkan terlalu literasi akan memicu individualisme dan tidak munculnya pencampuran perspektif untuk memperkaya makna. Menyeimbangkan keduanya pun menjadi hal yang penting. Diskusi mungkin bisa menjadi salah satu cara. Perhatikan bahwa diskusi merupakan tindakan lisan yang tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa dilandasi tradisi literasi dari setiap peserta diskusinya.
Sebelumnya disinggung bahwa sejak ditemukannya TV dan radio, dikotomi literasi dan lisan semakin ambigu, yang kemudian membuat kedua tradisi itu harus diredefinisi. Dengan berkembangnya teknologi informasi, ambiguitas-ambiguitas baru bermunculan menciptakan fenomena unik mengenai keadaan kultur masyarakat yang semakin “banci” dan tidak terbaca. Pada tulisan yang lain (Dalam Penjara Teknologi), saya telah membahas beberapa dampak berkembangnya teknologi dan memberikan terminologi virtual mind atau mental virtual sebagai keadaan masyarakat pengguna teknologi pada era informasi seperti sekarang.
Apa itu mental virtual? Secara umum ia bisa dikatakan sebagai mental yang cenderung membingkai diri dalam paradigma virtual yang terasing dari realita. Ketika mental virtual terbentuk, seseorang akan cenderung lebih merasa nyaman berada dalam dunia virtual ketimbang hidup dalam realita nyata yang sebenarnya. Salah satu ciri mental virtual adalah daya reaksi yang sangat kuat karena pikiran tidak terbiasa mencerna informasi dengan matang sebagai akibat dari terlalu banyaknya arus informasi yang mengalir setiap harinya. Teknologi informasi menjadi suatu teks raksasa dengan informasi luar biasa banyaknya. Akan butuh daya literasi yang tinggi untuk bisa membaca itu semua dalam pengolahan yang baik.
Terkait hal itu, perlu diketahui bahwa literasi memang memiliki 4 tingkatan yang menanjak, yakni performative, functional, informational, dan epistemic. Performative, sebagai tingkat literasi paling pertama, hanyalah kemampuan baca dan tulis secara tekstual, yang mana cukup bisa mengetahui apa yang bisa terbaca dari rangkaian aksara. Functional merupakan tingkat literasi yang mana teks sudah bisa digunakan secara pragmatis oleh pengguna. Informational terjadi ketika informasi bisa terakses dengan bahasa, dan terakhir, epistemic, sebagai tingkatan tertinggi, terjadi ketika informasi itu bisa ditransformasikan dan diinterpretasi lebih lanjut dengan dialog kritis terhadap teks. Tentu ketika berbicara literasi yang sesungguhnya, yang dimaksud adalah literasi tahap epistemic, walau terkadang literasi performative lebih digunakan untuk mengukur tingkat literasi dari suatu negara, seperti indeks literasi yang dimunculkan UNESCO yang mana mengukur berapa persen warga suatu negara berumur 15 tahun yang bisa baca dan tulis.
Ketika berbicara mengenai teks sebesar teknologi informasi, jika suatu masyarakat telah mencapai literasi epistemik, hal ini tidak akan jadi problematika, karena informasi akan diserap secara selektif. Namun dalam keadaan dimana masyarakat masih belum terbiasa menganalisis teks, termasuk fenomena teknologi, banjir informasi yang terjadi tiap menitnya akan diserap begitu saja ke dalam pikiran. Padahal, dengan arus informasi yang begitu cepat, tidak akan ada ruang yang banyak untuk berpikir dan berkontemplasi, sehingga segala sesuatu hanya akan mendapat respon singkat dari kepala dengan informasi dan pengetahuan seadanya. Inilah yang kemudian memicu daya reaktif masyarakat yang terpapar teknologi namun daya literasinya masih rendah.
Literasi ala teknologi informasi pun berubah menjadi apa yang disebut sebagai lisan tingkat kedua. Bagaimana kita chatting, diskusi di ruang daring, saling komentar dan memberi like, SMS-an, dan semacamnya hanya merupakan lisan yang tertulis. Ciri khas dari tradisi lisan adalah adanya ruang tanggapan multi arah dan tidak adanya ruang ekslusif yang mana pengguna dan teks mencipta makna melalui analisis kritis dan holistik. Teks pada tradisi literasi menampilkan dirinya secara utuh untuk dibaca, sedangkan pada tradisi lisan tidak, ia muncul secara bertahap melalui proses komunikasi. Cuplikan-cuplikan teks pada tradisi lisan menuntut akan adanya respon. Inilah yang sebenarnya terjadi pada era informasi, khususnya media sosial, yang mana selalu menimbulkan keinginan untuk merespon cepat. Perbedaan utama literasi dalam teknologi informasi adalah lisan yang dilakukan menggunakan perantara ketika tradisi lisan pada awalnya adalah komunikasi langsung. Inilah yang membuat ia disebut sebagai lisan tingkat kedua.
Walaupun sama-sama tergolong lisan, tradisi lisan tingkat kedua tidak bisa dilihat sama dengan lisan tingkat pertama. Pertama, lisan tingkat kedua mengaburkan batas antara ruang privat dan ruang publik, yang mana jadi ciri khas lisan tingkat pertama. Lisan tingkat pertama selalu mengutamakan ruang privat antar dua atau lebih individu untuk saling bertukar teks, sedangkan publisitas cenderung jadi milik tradisi literasi. Namun pada era informasi, walaupun ruang privat juga tercipta dengan private chat antar dua orang atau sebuah grup chat yang berisi orang-orang tertentu, ruang privat ini tetap bisa terbawa publik melalui status, post, dan lain sebagainya. Banyak hal yang menurut saya sendiri adalah konsumsi privat, dibuat publik, tanpa sadar bahwa ribuan atau jutaan orang lain bisa melihat itu. Fenomena lain yang saya lihat juga adalah ruang privat berupa grup chat terkadang kehilangan identitasnya dengan ketidakjelasan privasi yang tercipta dalam ruang tersebut. Kedua, lisan tingkat kedua diikuti dengan aliran informasi yang tak terbendung tiap waktunya , sehingga membuat lisan yang tercipta tidak pernah lengkap, hanya cuplikan-cuplikan yang terus berganti. Hal ini sangat berbeda dengan lisan tingkat pertama yang mana teks bisa menampilkan diri dengan lebih lengkap melalui komunikasi yang cukup tanpa ada distraksi teks lain.
Jika lisan memiliki tingkat, maka literasi pun juga, yang mana sama-sama dipicu perkembangan teknologi. Pada era informasi seperti sekarang, sumber pengetahuan tidak hanya berupa tulisan beraksara, namun bisa juga video atau suara. Apalagi dengan berkembangnya konsep e-learning, adanya audiobook, atau mulai banyaknya online course, entah sekedar melalui youtube atau situs tersendiri, teks berkembang menjadi sangat luas. Yang tetap perlu diingat adalah ciri utama tradisi lisan,yaitu adanya ruang dialog ekslusif antara pengguna dan teks yang mana interpretasi kritis terhadap makna bisa tercipta. Inilah tradisi literasi tingkat kedua, yang mana cikal bakalnya adalah radio dan televisi, yang mana teks menampilkan diri tanpa membuka ruang tanggapan.
Arsip, Pilar yang Terlupakan
Sekarang fokus kembali pada literasi, telah dikatakan sebelumnya bahwa ciri khas literasi adalah interpretasi makna dari teks. Dalam hal ini, teks berwujud dalam suatu objek material, berbeda dengan tradisi lisan yang mana teksnya adalah individu itu sendiri. Inilah kelebihan utama tradisi literasi, yang mana teks bisa diawetkan sedemikian rupa sehingga informasi dan makna yang terkandung di dalamnya bisa terjaga melintasi waktu. Dalam tradisi lisan, karena individu tentu kelak akan meninggal dunia, informasi dan makna dari setiap individu harus ditransfer terus menerus antar generasi agar bisa terjaga, itu pun jika tidak mengalami pergeseran makna. Teks dalam tradisi literasi yang terjaga ini lah yang kemudian bisa dijadikan definisi untuk arsip.
Arsip pada KBBI edisi IV didefinisikan sebagai dokumen tertulis yang mempunyai nilai historis, disimpan dan dipelihara di tempat khusus untuk referensi. Karena sebenarnya segala sesuatu yang ada pada saat ini berasal dari masa lalu, maka segala hal di dunia ini pasti punya nilai historis. Nilai historis di sini bisa diartikan sebagai semua informasi yang terkait dengan masa lalu. Ketika fokus pada teks sebagai dokumen tertulis, maka arsip adalah media literasi paling utama untuk merekam dan interpretasi semua informasi. Namun, tentu dokumen tertulis bukan hal yang ada begitu saja, ia diciptakan. Di sinilah pentingnya penciptaan teks itu sendiri ketimbang kemampuan membaca atau interpretasi. Kreasi teks di sini harus berlandaskan pemikiran kreatif, sehingga berpikir kritis dan kreatif merupakan keseimbangan ketika mencipta dan memahami teks.
Apapun informasi bisa dienkripsikan dalam bentuk teks, mulai dari gagasan hingga peristiwa. Ketika tradisi lisan terfokus pada memori untuk menyalurkan informasi, maka tradisi literasi terfokus pada arsip yang merekam itu dalam bentuk teks. Hal ini hanya akan terjadi bila tradisi literasi masyarakat sudah mencapai tahap epsitemik. Kenapa? Karena pada hanya pada tahap ini lah dialog kritis antara pembaca dan teks yang awalnya terjadi secara inklusif ditransformasikan lebih lanjut menjadi teks lain. Literasi hingga tahap informatif hanyalah literasi pasif, yang mana hanya melibatkan subjek sebagai pembaca, belum sebagai penulis atau pencipta teks. Ketika kultur untuk mencipta teks tidak tercipta, maka teks tidak pernah terproduksi sehingga tidak ada perkembangan berarti dalam informasi yang beredar. Padahal, berbicara mengenai literasi berarti berbicara bagaimana perannya dalam memicu perkembangan dengan menjaga informasi agar terus berputar dalam siklus reproduksi teks.
Setelah kultur membaca dan menulis itu sendiri sudah ada, akan menjadi percuma bila teks yang sudah ada tidak terjaga dengan baik. Di sini peran arsip masuk sebagai pilar ketiga literasi yang sering terlupakan. Membaca sebagai proses interpretasi teks, menulis sebagai proses penciptaan teks, dan arsip sebagai pengaturan terhadap teks, bersama-sama berada dalam siklus untuk menjaga agar arus informasi dan pengetahuan tetap berjalan sehingga peradaban berkembang dengannnya. Dari tiga pilar ini lah kita bisa mengatakan dengan tegas bahwa literasi memang pemicu berkembangnya peradaban.
Teks, yang mana terfokus pada dokumen tertulis, sebenarnya bisa diperluas, seperti yang sudah dibahas juga sebelumnya. Dalam hal ini, arsip bertransformasi tidak hanya menjadi kumpulan dokumen, tapi menjadi segala benda yang mengandung informasi masa lalu. Semua benda bersejarah adalah arsip, yang mana mengutuh bersama aspek-aspek lain yang terkait dengannya, apalagi jika hal ini merujuk ke suatu tempat. Misalkan saja borobudur dibuat ulang di tempat lain secara persis tanpa ada perbedaan sedikit pun, maka banyak informasi yang turut hilang juga karena konteks arsip tersebut dengan lingkungan dan tempatnya berubah dengan tempat yang berpindah. Inilah yang menjadi kekurangan teks dalam bentuk benda atau tempat. Ia tidak bisa direproduksi tanpa menghilangkan beberapa makna. Oleh karena itu, ketika berbicara mengenai arsip, kita cukup fokus pada arsip tertulis, atau mungkin jika perlu diperluas sedikit, arsip multimedia dalam bentuk digital. Selain inkripsi maknanya mudah terbaca, ia juga mudah untuk dikonservasi dan dijaga, beda dengan benda yang mana tidak bisa semudah itu “dibaca” dan disimpan.
Indonesia dan Literasi
Berbicara mengenai negeri ini tentu tidaklah mudah. Permasalahan yang ada di negeri ini begitu kompleks dan terkait satu sama lain sehingga sukar berbicara satu aspek tanpa menyinggung aspek yang lain. Hal yang paling mudah ditarik mundur dari akar permasalahan Indonesia adalah sumber daya manusianya, yang mana jika melihat keadaan sekarang ke belakang, memiliki tingkat literasi yang rendah. Hanya sedikit dari masyarakat Indonesia yang telah mencapai tahap epistemik.
Kenapa tingkat literasi menjadi poin penting dalam permasalahan Indonesia? Karena tingkatan literasi terkait dengan bagaimana subjek merespon teks secara luas. Ketika Indonesia hanya bisa mencapai tahap informasional, maka sudah menjadi hal yang wajar bila kita menjadi masyarakat yang pasif dan tidak bisa memahami keadaan secara kritis. Beragam perubahan kita tanggapi dengan gagap dan bingung, bahkan cenderung reaktif. Kita akan dengan mudah mengikuti begitu saja semua tren yang ada karena kita cenderung menerima semua informasi apa adanya tanpa mencipta dialog kritis dengan pikrian. Hal ini menjadikan kita bangsa yang sangat mudah diperalat dan dipermainkan oleh bangsa-bangsa bertingkat literasi epistemik.
Ketika melihat secara kultural, Indonesia memang dari awal telah berada dalam simalakama. Tradisi lisan yang mengakar dalam tubuh masyarakat Indonesia ditransformasi ‘paksa’ menjadi tradisi tulisan dengan terbentuknya republik dengan sistem yang sangat literasi. Kenapa bisa saya bilang ‘paksa’, karena pada dasarnya ketika republik ini dibangun oleh kelompok intelektual (yang bertradisi literasi tentunya), tidak semua masyarakat siap untuk sistem itu. Menjadi dilema memang, karena melawan penjajah yang literatif tentu saja harus dengan senjata literasi juga. Ketika kemudian masyarakat berusaha untuk beradaptasi dengan sistem literasi, belum sempurna transisi ini, Indonesia sudah ditawarkan dengan ragam pembangunan dan impor teknologi dari luar sebagai hasil dari orde baru. Tentu ketika masyarakat tidak siap secara mental dan kultural, kemajuan teknologi akan ditanggapi dengan gagap dan sekali lagi menciptakan transisi yang tidak sempurna, bahkan hingga saat ini. Ketika di atas sana Indonesia diproyeksikan untuk banyak hal, seperti MEA dan lain sebagainya, di bawah sini masyarakat tertatih-tatih mengikuti transisi yang tidak pernah terkejar.
Lalu bagaimana? Ya melihat akar utama dari hal ini, tentu yang paling penting adalah memperbaiki literasi masyarakat Indonesia. Tapi sayang, hal ini justru diperparah oleh sistem, yang mana sejak Sekolah Dasar murid dibiasakan untuk menerima informasi begitu saja, bukan diajarkan “membaca” dalam arti dialog kritis terhadap teks. Kultur kita yang masih terbawa tradisi lisan pun juga tidak mendukung tumbuhnya literasi. Tradisi literasi yang sesungguhnya baru benar-benar ditemui di dunia pendidikan tinggi. Namun, ketika 19 tahun dibiasakan untuk pasif terhadap teks, bukan hal yang mudah untuk kemudian dalam 4 tahun kuliah membangun jiwa literasi dalam diri. Dapat saya lihat sendiri di ITB, yang seharusnya merupakan representasi kampus ideal di Indonesia, budaya literasi di mahasiswanya tidak terbentuk banyak. Hal ini diperparah dengan paradigma pembelajaran kampus yang mulai pragmatis. Tidak ada alasan untuk kampus teknik sebenarnya, karena semua ilmu merupakan teks yang selalu bisa diliterasikan.
Literasi sudah mencakup banyak hal mengenai kualitas dasar manusia, bagaimana kita berpikir kreatif untuk mencipta teks dan bagaimana kita berpikir kritis untuk memahami teks. Pengetian teks di sini memang bisa diperluas, namun ada kelebihan utama lain dari teks tertulis, bahwa ia mengabadikan gagasan secara eksplisit. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, teks tertulis merupakan teks yang paling mudah dibaca maknanya ketimbang yang masih terenkripsi dalam bentuk audio atau visual lain. Teks tertulis mengejawantahkan makna-makna yang tak terbaca pada teks lain sehingga ia akan lebih awet dan terabadikan, apalagi jika ia berupa ciptaan gagasan. Maka seperti kata pram atau penulis-penulis lainnya, menulis berarti memperpanjang hidup.
Tapi, seperti apa kata pak Acep Iwan Saidi dalam diskusi tempo hari lalu, hal ini sudah menjadi permasalahan sistemik dan bukan hal yang mudah untuk mengubahnya karena pasti akan berbenturan dengan banyak kepentingan. Maka seperti hasil diskusi tersebut, mulailah perubahan dari akar rumput! Bermula dari diri sendiri, bagaimana mulai menulis untuk yang belum pernah menulis dan menjaga konsistensi untuk yang sudah, lalu kemudian ke lingkungan, bagaimana kita secara perlahan mengajak, menginspirasi, dan memberi contoh, agar orang-orang sekitar mengikuti hal yang sama, baru kemudian bertahap terus hingga lingkaran pengaruh ini meluas.
Maka apa yang bisa saya lakukan sebagai anak matematika? Ya terus konsisten menulis, dengan harapan teruntai di tiap kata-katanya, bahwa akan ada orang yang terinspirasi dan mengikuti, dan kelak bangsa ini akan terbangun dengan sendirinya melalui budaya literasi yang tumbuh bersama beradaban!
Mari berliteraksi!
Salam Pembebasan.
Menteri Pusat Studi Arsip dan Kajian Kebijakan Kabinet KM ITB 2016
(PHX)
Nb:
Jujur, bingung mencari judul. Maka ya sudah, literasi memang tengah mencari arti, yang hilang dalam hiruk pikuk peradaban yang ia bangun sendiri.